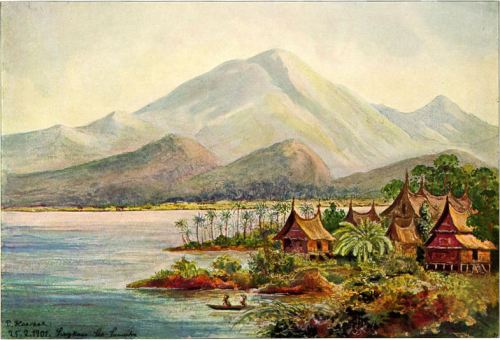Penyerbuan Dewang Parakrama
Dari pihak dalam negeri, ketidaksenangan terhadap pemerintahan Maharaja Dewana dan Raja Bagewang, ditimbulkan oleh Dewang Palokamo Pamowano (Dewang Parakrama Parmawana) atau Dewang Parakrama. Pangeran ini seorang dari Wangsa Malayupura yang tinggal di Darmasyraya. Jika di Pagaruyung para Pangeran (Puto-Puto) dan raja-raja dari Wangsa Melayupura telah menjadi pemeluk agama Islam yang taat sejak Daulat Yang Dipertuan Maharaja Sakti I, maka Dewang Parakrama masih menganut agama Budha Mahayana dari Tarikat Tantrayana. Sebagian keterangan tradisi mengatakan bahwa sebenarnya Pangeran ini tidak memeluk agama alias Pagan. Pangeran ini dari pihak kakek dan neneknya (dari belahan ayah maupun belahan ibu) sudah berada di kawasan sekitar Ulu Tebo. Kakeknya (ayah dari ayahandanya) menjadi Raja Ulu Tebo yang kemudian diganti ayahandanya. Untuk selanjutnya Dewang Parakrama menggantikan.
Dewang Parakrama tidak pernah bersetia kepada Raja Ranah Sekelawi sebagai atasan yang ditunjuk Pagaruyung. Sebaliknya raja ini juga tidak menyatakan diri di bawah Raja Tebo yang merupakan wilayah bawahan Raja Jambi. Raja ini menyatakan dirinya sebagai raja merdeka, dan berdaulat sendiri. Untuk menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatannya, raja ini memaklumkan dirinya sebagai Maharaja Swarnabhumi yang sah dengan menduduki Siguntur di Darmasyraya. Hal itu di mungkinkan karena sebelumnya dengan diam-diam Raja Pamowano (Dewang Parakarma) mengadakan perjanjian persaudaraan dengan Portugis, orang Rupik Sipa tokah dari Tanah Alang Buwana. Portugis berhasil merebut Malaka 1511 M, dan ini dijadikan sebagai batu loncatan untuk kemudian dengan memperalat kaki tangannya (Raja Pamowano) menguasai Sumatera, dengan mencoba merebut Pagaruyung. Emas berbungkal diserahkan/dijual raja ini kepada orang Rupik sebagai imbalannya.
Dengan demikian semua kawasan Darmasyraya (Tiga Laras) dapat ditundukkannya. Dari Darmasyraya, Dewang Parakrama memasuki kawasan Jambi. Pasukan Jambi memeberikan perlawanan. Pertempuran dahsyat dengan pasukan Jambi berlangsung dengan hebatnya di Tebo. Pasukan Jambi kewalahan, kemudian mundur dan kawasan kuala sungai Tembesi yang direbut oleh Dewang Parakrama. Tetapi kemudian kembali balik menyerang Tebo. Pasukan Dewang Parakrama dapat di pukul mundur ke hulu sungai Tembesi. Namun kawasan hulu Tembesi bahkan bebe rapa kawasan di Kerinci dapat direbutnya. Untuk selanjutnya Dewang Parakrama kembali ke Darmasyraya, dan dari sini sebuah pasukan besar disiapkan. Dengan pasukan besar ini Dewang Parakrama memasuki Luak Tanah Datar.
Pada tahun kl. 1514, melalui sebuah pertempuran besar, Pagaruyung khususnya dan Luhak Tanah Datar umumnya jatuh ke tangan Dewang Parakrama. Maharaja De wana dan keluarga istana lainnya cerai berai akibat penyerbuan Dewang Parakrama yang dengan tiba-tiba sudah sampai saja ke istana. Maharaja Dewana sempat lolos dan menyingkir dengan dikawal sepasukan bersenjata ke Lipat Kain dan di Kampar Kiri Sedangkan permaisuri yakni Dewi Ranggowani, bersama Puti Reno Bulian (putri baginda), sudah diselamatkan terlebih dahulu ke Koto Anau Kubuang Tigo baleh. Untuk selanjutnya Dewang Parakrama menjadi raja di Pagaruyung dan dike nal dengan nama Maharajo Palokamo atau Maharaja Parakrama.
Pemerintahan Maharaja Parakrama (1514- 1524)
Maharaja Parakrama, hanya menguasai Luak Tanah Datar bagian utara dan ti mur, disamping kawasan Darmasyraya. Maharaja ini dengan segera membuka hu bungan resmi dengan Portugis di Melaka. Sebuah delegasi dipimpin oleh tiga orang pemuka kerajaan dikirim ke Melaka. Ketiganya adalah pemimpin-pemimpin penga nut Sekte Tantrayana agama Budha Mahayana. Karena Sekte Tantrayana merupakan sekte yang mengandalkan diri lewat mantra-mantra, karena itu dianggap penganutnya pemeluk kepercayaan animisme (Pagan) oleh Portugis. Sehingga pihak Portugis mencatat Minangkabau penduduknya pada saat itu tidak beragama, karena ketiga utusan yang datang ke Malaka menemui pimpinan Portugis itu penganut keperca yaan yang masih pagan (animisme). Tambo mengisyaratkan tentang raja ini , bahwa “agama orang Makah tak disukainya, agama lamapun malas memakai.”
Sebuah berita Portugis berasal dari penulis Jorge de Brito pada pertengahan abad ke-16 menceritakan: bahwa utusan yang dipertuan Minangkabau yang berkun jung ke Bandar Malaka masih “pagan”. Berita itu kiranya dapat dijadikan petunjuk, bahwa hingga pertengahan abad ke-16 agama Islam belum lagi berkembang di Alam Minangkabau, sekurang-kurangnya yang dipertuan Minangkabau dan anggota keluarga terdekatnya belum lagi menganut agama itu. (INI CERITA PORTUGIS).
Dari berita ini banyak pakar, penulis sejarah kita ikut menerima begitu saja bah wa Minangkabau pada abad ke 16 belum Islam. Pada hal Islam telah masuk ke Minangkabau dalam beberapa tahap perkembangannya sejak dari abad ke 7-8 M dengan masuknya komunitas Arab di Pesisir Barat Sumatera Barat (baca Hamka) kemudian pada abad ke 12 -13 M (naik dari Indrapura ke Pariangan) dan di awal abad ke 15 M sejak Yang Dipertuan Raja Nan Sakti I di Bukit Batu Patah murid Syaikh Maghribi, dan ayah kandung Daulat Yang Dipertuan Puteri Panjang Rambut II (Bundo Kandung-Mande Rubiah). Sampai kepada puncak kesempurnaan dan meratanya Islam di Minangkabau di zaman Syaikh Burhanuddin Ulakan Pariaman.
Hal ini juga terlihat dari sikap dan tindakan Maharaja Parakrama yang bertindak keras terhadap peniaga-peniaga beragama Islam. Ialah dengan cara melarang dari kalangan peniaga itu berdagang ke wilayah kerajaan .Yang dibenarkan hanyalah peniaga-peniaga beragama Budha Mahayana ataupun Hindu. Begitu juga peniaga-peniaga Minangkabau yang berada di luar negeri tetapi sudah memeluk Islam, dila rang datang berkunjung ke kampung halaman, apa lagi untuk berniaga. Sementara itu peniaga-peniaga dari kalangan bangsa Portugis pergi ke pelabuhan-pelabuhan utama wilayah timur untuk membeli emas dan membawanya ke Melaka. Penduduk yang beragama Islam ditindas, dan agama Budha Mahayana dari tarikat Tantrayana disebar luaskan kembali. Pendeta-pendeta utama berada di sekeliling baginda di Istana Pagaruyung.
Sementara itu kawasan pantai barat dicoba untuk direbut. Tetapi pada mulanya gagal. Barulah setelah mengerahkan jumlah pasukan yang cukup besar, beberapa kawasan di sepanjang pantai barat Minangkabau akhirnya jatuh ke tangan kekuasaan Maharaja Parakrama. Namun tak lama, kemudian lepas lagi. Berlainan dengan raja-raja sebelumnya, perniagaan emas dilakukan oleh orang-orang kerajaan dan men jualnya langsung ke tangan peniaga-peniaga asing yang datang ke pelabuhan pelabuhan dan pasar pasar pengekspor di wilayah timur. Semua keuntungan dan cukai diserahkan kepada Maharaja Parakrama untuk kepentingan kerajaan.
Luhak Limapuluh yang berhubungan rapat dengan kawasan timur, sejauh ini menjadi penghalang dari perniagaan yang diatur baginda. Maka Maharaja Parakrama mengerahkan tentaranya ke Luhak Limapuluh. Setelah bertempur mati-matian akhirnya Luhak Limapuluh pun jatuh ke tangan Pagaruyung. Suatu pertempuran di Mungka terjadi, dan pasukan Pagaruyung (pasukan Maharaja Parakrama) mencapai kemenangan. Mulai saat itu, kawasan rantau timur (termasuk Darmasyraya), Luhak Limapuluh dan bagian timur serta utara Luak Tanah Datar berada dibawah kekuasaan Maharaja Parakrama yang berkedudukan di Pagaruyung. Sedangkan kawasan Luhak Agam, kawasan Kubuang Tigobaleh (bagian selatan Luak Tanah Datar) dan wilayah rantau barat tidak berhasil direbut Pagaruyung (Maharaja Parakrama). Wilayah yang tak dapat dikuasai itu, tetap mengakui Maharaja Dewana sebagai Maharaja Suwarnabhumi – Minangkabau yang waktu itu mengungsi ke Koto Anau.
Perang Melawan Maharaja Parakrama
Untuk beberapa lama, seperti terjadi penghentian permusuhan Maharaja Parakrama berdaulat di wilayah kekuasaannya sedangkan Maharaja Dewana diakui untuk wilayah-wilayah yang masih setia kepadanya. Yang menunjukkan permusuhan di antara kedua belah pihak, ialah para pemimpin utama kerajaan ada yang pindah ke Luak Agam dan ada yang pindah ke Kubung Tigabelas. Datuk Nan Baranam di Istana Gudam beserta keluarga kerajaan dan Datuak Nan Batujuah di Istana Balai Janggo meninggalkan Pagaruyung. Yang mendampingi Maharaja Parakrama, di istana Balai Gudam benar-benar orang yang ditunjuk oleh Maharaja Parakrama. Seterusnya tidak diperkenankan siapapun dari Luak Agam, Rantau Mudik (Rantau Barat) dan Kubung Tigabelas memasuki wilayah yang dikuasai Maharaja Parakrama. Keadaan seperti api di dalam sekam.
Suatu gejolak timbul, dikarenakan pasukan bawahan Maharaja Parakrama me masuki wilayah Kubung Tigabelas. Ialah pasukan dari Maharaja itu yang ditempatkan di Saningbakar. Maka para pemuka Kubung Tigabelas melakukan perundingan di Supayang. Kemudian menghubungi Luak Agam. Akhirnya datanglah pihak Luak Agam. Kesepakatan kedua belah pihak ialah melakukan pembebasan Pagaruyung. Dengan segera baik di Luak Agam maupun di Kubung Tiga belas disusun pasukan yang kuat, untuk membebaskan Pagaruyung. Kedua pasukan dengan segera melaku kan penyerangan ke bagian utara Luak Tanah Datar.
Pertempuran yang berkobar tahun kl. 1524 ialah tahun ke-10 (sepuluh) pemerintahan Maharaja Parakrama, berkecamuk di Tanah Datar. Dalam pertempuran dah syat yang memakan waktu berhari-hari, akhirnya pasukan Maharaja Parakrama mun dur ke Darmasyraya. Tetapi pasukan inipun dapat diusir dari kawasan ini dan dikejar ke hilir Batang Hari. Setelah dihubungi Kerajaan Jambi, pasukan Jambi pun memu diki sungai sehingga pasukan Maharaja Parakrama terjepit.
Maharaja Parakrama sendiri menyingkir ke Jambi, tetapi dikejar oleh pasukan Jambi yang dipimpin oleh Panglima Kilangan Besi. Maharaja Parakrama membawa pasukannya ke Kerinci. Tetapi di Kerinci, baginda ini tertangkap dan dibawa ke Jambi. Di Jambi, Maharaja Parakrama diadili sebagai penjahat dan dijatuhi hukuman mati. Maharaja Parakrama dihukum mati atas titah Raja Jambi Rangkayo Hitam, sekaligus hukuman mati itu menandai mulainya kedamaian, baik bagi masyarakat Jambi sendiri maupun bagi masyarakat Kemaharajaan Swarnabhumi Pagaruyung.
Maharaja Dewana Kembali Bertakhta dan Portugis Menyerbu.
Pada tahun kl. 1525 Maharaja Dewana kembali bertakhta. Permaisuri dan putra-putra baginda dijemput ke Koto Anau, dan kembali berdiam di istana Melayu Kampung Dalam di Gudam Pagaruyung. Namun begitu baginda kembali bertakhta, Portugis mengirim ekpedisi militernya untuk merebut tambang emas di kawasan wilayah barat. Pasukan Portugis mendarat di Pasaman, di Pariaman, di Muara Pesisir (Rantau Empat Lurah), di Carocok Gaduang Intan, Sungai Nyalo, Salido dan di Indrapura. Pertempuran-pertempuran dahsyat terjadi. Portugis mengerahkan bajak laut berbangsa Cina dan India (Sipahi) untuk membantunya. Beberapa kerajaan kecil seperti Taluak Sinyalai Tambang Papan, Sungai Nyalo, Taluak Lelo Jati, Palinggam Jati di sepanjang pantai barat tenggelam karena aksi bumi hangus dan bumi angkat Portugis. Walaupun beberapa kerajaan kecil itu mulanya berupaya melawan namun sia-sia belaka.
Pemerintahan Pagaruyung mengirim pasukan tempur ke pesisir barat dan berhasil menghalau Portugis dari wilayah Pasaman. Berbarengan dengan itu, pihak Portugis juga satu demi satu meninggalkan pos-pos mereka di sepanjang pantai barat. Maharaja Dewana berusaha untuk membangun kembali kemaharajaan Suwarnabhumi. Namun pada waktu itu Aceh muncul di ujung utara pulau Sumatera. Atau tepatnya di ujung barat laut dari pulau yang memanjang ke tenggara. Maharaja Dewana tidak memandang kehadiran Aceh sebagai saingan, apalagi musuh, tetapi diterima sebagai negara sahabat. Banyak dari kalangan warga Kemaharajaan Swarnabhumi Pagaruyung (orang Minangkabau) yang pergi ke Aceh dalam rangka memperdalam ilmu agama Islam, disamping berniaga. Seperti diketahui juga, Aceh pada zaman itu merupakan serambi Mekah untuk tujuan melanjutkan perjalanan ke tanah suci. Walaupun sebagian ada yang mengambil jalan darat lewat Malaysia, Birma, India dan seterusnya menuju Jazirah Arab. Hubungan itu semakin erat dengan diambilnya adinda Sultan Aceh yang dikenal dengan nama Putri Keumala sebagai permaisuri Maharaja Dewana.
Perkawinan berlangsung dan pesta besar dilangsungkan di Aceh dan Pagaruyung. Di Aceh, Maharaja Dewana membagi-bagikan emas kepada para pembesar dan pemuka Aceh, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah sepanjang yang hadir pada pesta perkawinan. Karena emas yang cukup banyak dibawa dari Pagaruyung habis, maka Maharaja Dewana meminjam kepada Baitul Mal Kesultanan Aceh, dengan janji begitu sampai di Pagaruyung, akan dikirim petugas khusus untuk mengantarkannya. Tetapi sesampai di Pagaruyung, bagindapun mengadakan pesta perkawinan yang lebih besar dan setiap pembesar yang hadir ditambah dengan tamu-tamu kerajaan diberi hadiah emas. Pengeluaran baginda baik ketika di Aceh maupun ketika di Pagaruyung menimbulkan kebangkrutan kerajaan.
Putri Keumala langsung ke Pagaruyung setelah pesta pernikahan di Aceh. Sebelum sampai baginda dan sang putri ke Pagaruyung, terlebih dahulu Dewi Ranggowani sang permaisuri, (istri I) meninggalkan Pagaruyung dan kembali ke Koto Anau. Juga ikut serta Putri Reno Bulian, yakni putri baginda dan sang Dewi. Maharaja Dewana menjadi marah, bahkan mengumumkan bahwa mulai saat kedatangan baginda dari Aceh, Dewi Ranggowani hanyalah seorang istri biasa bagi baginda. Sedangkan sebagai raja puteri (permaisuri) digantikan oleh Putri Keumala dengan nama Putri Reno Kumalo (Putri Ratna Kumala). Baginda juga membuat keputusan-keputusan tanpa bersidang dulu dengan Besar Empat Balai. Akibatnya, Besar Empat Balai menyatakan non-aktif dan tidak akan turut campur soal kerajaan. Sejak itu Maharaja Dewana mengendalikan kerajaan sendirian. Bersamaan dengan itu Kubung Tigabelas kembali kepada kehadirannya semula untuk tidak tunduk kepada pemerintahan kerajaan. Tindakan Kubung Tigabelas itu disusul oleh Tanjung Sungayang.
Putri Keumala langsung ke Pagaruyung setelah pesta pernikahan di Aceh. Sebelum sampai baginda dan sang putri ke Pagaruyung, terlebih dahulu Dewi Ranggowani sang permaisuri, (istri I) meninggalkan Pagaruyung dan kembali ke Koto Anau. Juga ikut serta Putri Reno Bulian, yakni putri baginda dan sang Dewi. Maharaja Dewana menjadi marah, bahkan mengumumkan bahwa mulai saat kedatangan baginda dari Aceh, Dewi Ranggowani hanyalah seorang istri biasa bagi baginda. Sedangkan sebagai raja puteri (permaisuri) digantikan oleh Putri Keumala dengan nama Putri Reno Kumalo (Putri Ratna Kumala). Baginda juga membuat keputusan-keputusan tanpa bersidang dulu dengan Besar Empat Balai. Akibatnya, Besar Empat Balai menyatakan non-aktif dan tidak akan turut campur soal kerajaan. Sejak itu Maharaja Dewana mengendalikan kerajaan sendirian. Bersamaan dengan itu Kubung Tigabelas kembali kepada kehadirannya semula untuk tidak tunduk kepada pemerintahan kerajaan. Tindakan Kubung Tigabelas itu disusul oleh Tanjung Sungayang.
Penyerbuan Aceh
Hutang Maharaja Dewana kepada Baitul Mal Kesultanan Aceh ditagih oleh Bendahara yang memegang kepemimpinan Baitul Mal itu kepada baginda. Tagihan itu melalui surat yang ditujukan kepada Putri Ratna Kemala. Tagihan pertama setelah baginda setahun selepas pernikahan. Namun baginda menjanjikan akan membawa kepada sidang Besar Empat Balai untuk dapat ditanggulangi atau dicarikan jalan keluarnya sehingga hutang terbayar. Besar Empat Balai tidak satupun memenuhi panggilan bersidang dari baginda. Tiga bulan berselang hutang itu tidak ditagih lagi.
Namun setelah tiga bulan itu, datang kembali tagihan untuk kedua kalinya. Maharaja amat gusar, karena harta benda yang ada di Pagaruyung tidak ada yang berarti untuk pembayarnya. Namun baginda membalas langsung ke Aceh dengan janji agar pengurus Baitul Mal bersabar. Dan baginda akan membayar dengan segera, begitu pungutan yang dilakukan dari pelabuhan-pelabuhan yang ada terlaksana. Baitul Mal kemudian masih memberi kesempatan kepada baginda dan tiga bulan lagi pun berlalu.
Kali ini Baitul Mal kembali mengirim surat tagihan yang juga dialamatkan ke pada Putri Kemala. Sang Putri merasa malu dan mengutarakan langsung kepada baginda. Tetapi Maharaja Dewana marah, dan menganggap sang putri terlalu membesar-besarkan persoalan. Pertengkaran mencapai puncaknya, ketika Maharaja mengusir sang putri. Putri Kemala bersedia berangkat meninggalkan Pagaruyung jika diceraikan langsung oleh baginda. Karena marahnya, maka bagindapun menceraikan sang permaisuri. Putri Kemala setelah bermalam di rumah seorang teman sejawat, dengan beberapa pengiring yakni dayang-dayang yang dibawa dari Aceh, meninggalkan Pagaruyung dan sampai di Koto Gadang Luak Agam. Di Koto Gadang, sang putri berdiam untuk sementara dan mengajar para gadis bertenun, menerawang dan menyulam.
Utusan yang dikirim Maharaja Dewana yang membawa pesan baginda agar sang putri kembali datang berkali-kali, namun ditolak. Sementara itu sang putri mengirim utusan khusus ke Aceh untuk menemui Sultan Aceh, mengabarkan nasib yang menimpa dirinya. Sultan Aceh bukan main marahnya. Pada tahun kl. 1528, tiga tahun setelah pernikahannya diusirnya sang putri dari Pagaruyung, dengan segera memanggil para mentrinya yang dipimpin oleh Wazir, atau Perdana Mentri Kesultanan Aceh. Dikirimlah suatu pasukan khusus untuk menjeput sang putri ke Koto Gadang Agam. Namun ketika sampai di Koto Gadang, sang putri telah berangkat terlebih dahulu dan sampai di Natal. Di Natal sang putri diterima oleh Raja Natal. Nantinya dengan restu Sultan Aceh, sang putri atau Putri Kemala menjadi permaisuri dari Raja Natal.
Seterusnya pasukan Aceh dikirim ke Bandar Muar (Tiku), dan seorang Khalifah yakni wakil dari Sultan Aceh ditempatkan di sana . Bandar Muar dirobah nama nya menjadi Bandar Khalifah. Kemudian tentara Aceh juga ditempatkan di Pariaman, di Padang, di Bayang, Painan dan Indrapura. Pasukan Aceh dalam waktu cepat menguasai bagian barat dari Kemaharajaan Suwarnabhumi Pagaruyung. Pada tahun kl. 1539 hampir seluruh pantai barat Minangkabau dari Bandar Khalifah sampai Indrapura jatuh ke tangan Aceh. Awal tahun 1539 itu pula Aceh menundukkan kerajaan–kerajan nagari. Mulai saat itu di wilayah kekuasaan Aceh di pantai barat Minangkabau, tidak lagi memiliki rumah bergonjong seperti di pedalaman dan kawasan lain, tetapi menggantinya dengan “rumah berlangkan” yang disebut rumah gadang “Surambi Aceh”.
Kedudukan Aceh di pesisir barat disahkan oleh Pagaruyung setelah berlangsung perundingan antara Kesultanan Aceh dengan Pagaruyung atas inisiatif Raja Bagewang yang mengambil alih permasalahan dari pihak Pagaruyung. Ditetapkan kawasan pesisir barat (Rantau Mudik) terkecuali Pasaman, dikuasai oleh Aceh. Untuk itu pihak Aceh tidak akan mencampuri pemerintahan kerajaan dan nagari yang telah ada. Di wilayah kekuasaan ini, Aceh memiliki hak monopoli perniagaan, dan setiap hasil dari pesisir barat yang dikuasai Aceh dikirim ke luar negeri melalui Aceh. Sebagai imbalannya, Pagaruyung dibebaskan dari segala hutang piutang.
Maharaja Dewana Turun Takhta
Kehilangan wilayah pesisir barat Minangkabau, dianggap karena “ulah” Maharaja Dewana yang dikenal dengan gelar Daulat Tuanku Maharaja Sakti seperti kakek moyangnya. Gelar ini diwarisi dari kakek moyangnya Daulat Yang Dipertuan Raja Nan Sakti (I) ayah kandung Putri Panjang Rambut II yang kemudian mewarisi takhta kerajaan sebagai Daulat Yang Dipertuan Putri Raja Alam Minangkabau.
Selepas perundingan dengan Aceh, para pemuka kerajaan menolak untuk bekerjasama dengan Maharaja Dewana. Tetapi tidak satupun yang mengingini Maharaja Dewana untuk turun takhta. Namun Maharaja Dewana tidak mampu untuk mengendalikan kerajaan, karena setiap titah yang dikeluarkan baginda tak satupun dari masyarakat yang mematuhinya. Setiap nagari mengurus diri mereka sendiri.
Akhirnya Maharaja Dewana menyatakan pengunduran dirinya. Maharaja Dewana turun takhta sekitar tahun 1539 M. Baginda setelah turun takhta sebentar menjenguk keluarga ke Koto Anau. Untuk selanjutnya berangkat meninggalkan segala kemegahan dan keluarga yang ada. Baginda berangkat ke Pagar Dewang Tanah Kahyangan dan berkhalwat di sana.
Kenapa berkhalwat harus ke Pagar Dewang … ? Kenapa tidak di Pagaruyung Gunung Marapi saja ….? Apa hubungan khalwat dengan Pagar Dewang…yang terletak jauh di ujung Pesisir Barat bagian Selatan yang dikenal juga dengan wilayah Kerajaan Kesultanan Indrapura ? Apakah seorang raja Pagaruyung ini sajakah yang pernah pergi berkhalwat ke Pagar Dewang … ? Banyak pertanyaan muncul dari kalangan pemerhati yang menyimak misteri ini.
Baginda digantikan oleh putra baginda yakni Dewang Sari Megowano dari keturunan Istano Gudam yang naik takhta dengan gelar Daulat Yang Dipertuan Rajo Maharajo, atau Raja Maharaja. Sri Baginda Maharaja Dewana dengan Putri Kemala tidak mempunyai keturunan. Dengan Dewi Ranggowani mempunyai putra putri yakni Dewang Sari Megowano, Puti Reno Bulian (permaisuri Raja Koto Anau), Puti Reno Kayangan Pagadewi (Permaisuri Raja Sungai Nyalo di Koto XI Tarusan), dan Puti Reno Mahligai Cimpago Dewi (permaisuri Raja Sungai Tarab Dewang Patualo Sanggowano Rajowano Datuk Bandaharo Putiah (VI). Dan secara khusus disebut juga oleh anak kemenakan beliau sebagai “Datuk Gudam” (Datuk dari Balai Gudam).
Dari hubungan kekeluargaan ini jelas pula terkait erat hubungan kerajaan Koto Anau, kerajaan Sungai Nyalo di Koto XI Tarusan dengan Datuk Bandaro Putih VI yang kemudian menjadi Raja Alam Minangkabau. Ketiga kerajaan ini menjadi kekuatan utama dalam melumpuhkan Portugis di Pesisir Barat Sumatera, dan ini tidak terlepas dari kordinasi kekuatan dan diplomasi intelektual yang dilakukan Raja / Sultan Kerajaan Kesultanan Indrapura zaman itu. Dibalik hubungan kerajaan, sebenarnya mereka memiliki hubungan kekerabatan yang amat dekat.
Kenapa sejarah ini dihilangkan? Lalu muncul di abad 16 Maharaja Alif yang dibesar-besarkan … ? Inilah pertanyaan besar, seakan akan sejarah Minangkabau Pagaruyung hanya dimulai dari Maharaja Alif dan menganggap pula bahwa Islam baru berkembang di zaman raja ini … sebelumnya bagaimana … ? Inilah sejarah Minangkabau Pagaruyung yang terputus (sekira 2 abad) sejak Ananggawarman (putra Adityawarman) abad 14 sampai munculnya Maharaja Alif (abad 16). Ada bagian sejarah “Minangkabau Pagaruyung” yang sengaja atau tidak sengaja hilang dalam perjalanan kemelut sejarahnya …. Semoga kita mendapatkan titik palito kembali.